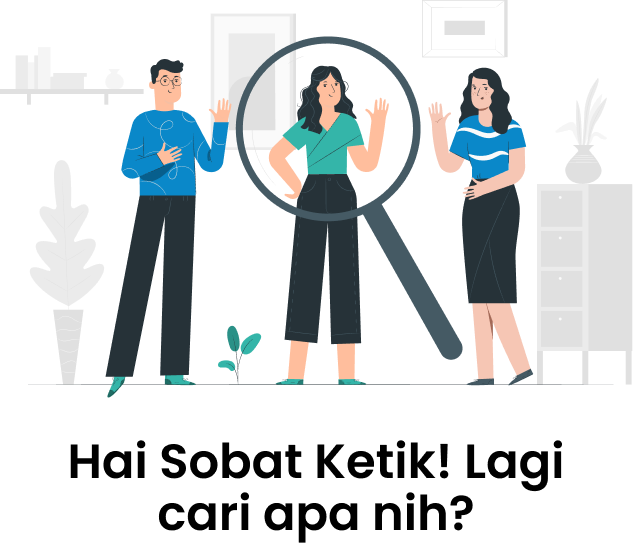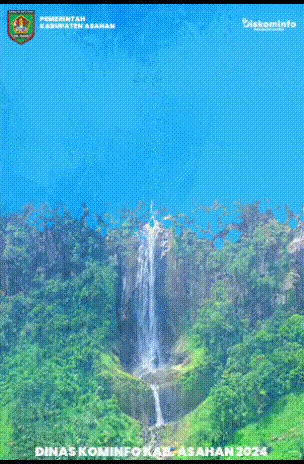Dalam politik, Pilkada adalah panggung yang dipenuhi oleh aktor-aktor yang bermain dalam skenario kekuasaan. Namun, di balik gemerlapnya janji-janji kampanye, ada sebuah paradoks yang senantiasa terulang.
Mereka yang berjuang di garis depan, tim sukses yang bekerja tanpa lelah di desa-desa, sering kali menjadi korban dari sistem yang lebih besar, sementara para pegawai yang mendapatkan jabatan justru menuai keuntungan pasca Pilkada. Persis di sini kita perlu pengendapan tentang makna kesetiaan dan kekuasaan.
Menyitir pemikiran Aristoteles, politik adalah seni tertinggi karena ia berhubungan dengan kebaikan tertinggi—yaitu eudaimonia, atau kehidupan yang baik.
Namun, dalam kenyataannya, politik sering kali melenceng dari tujuan idealnya. Ketika seseorang berjuang untuk memenangi kontestasi kekuasaan, baik dalam Pilkada maupun pemilihan lainnya, ia tidak semata-mata mencari kebaikan bersama, tetapi juga mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Dalam konteks ini, tim sukses memainkan peran yang krusial sebagai alat, bukan sebagai tujuan.
Tim sukses, dalam kacamata utilitarianisme, diperlakukan seperti instrumen. Mereka digunakan selama proses kampanye untuk mengumpulkan suara, meyakinkan masyarakat, dan berjuang tanpa lelah demi kemenangan pasangan calon.
Namun, setelah kemenangan tercapai, nilai instrumental mereka berkurang. Seperti alat yang telah digunakan, mereka tidak lagi dianggap penting oleh pemenang, yang kini lebih fokus pada pembagian kekuasaan dalam lingkaran yang lebih dekat dan lebih strategis.
Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialis, berbicara tentang konsep kejatuhan menjadi objek atau derealization—proses di mana manusia tidak lagi dipandang sebagai subjek otonom yang memiliki nilai, melainkan sebagai objek yang diperalat. Dalam konteks Pilkada, tim sukses sering kali terjebak dalam fenomena ini.
Mereka direduksi menjadi alat bagi para calon, sekadar perpanjangan tangan dalam permainan kekuasaan. Ketika tujuan politik tercapai, eksistensi mereka, sebagai subjek yang otonom, terhenti. Mereka menjadi "tidak ada" dalam struktur kekuasaan yang mereka bantu ciptakan.
Setelah kemenangan diraih, distribusi kekuasaan lebih sering diberikan kepada pegawai birokrasi yang memiliki nilai strategis bagi kelangsungan kekuasaan. Mereka yang telah bekerja keras demi kemenangan calon, dengan harapan akan mendapat imbalan setimpal, mendapati diri mereka ditinggalkan.
Dalam perspektif Machiavelli, hal ini bisa dianggap sebagai langkah pragmatis. Kekuasaan harus dipertahankan dengan aliansi strategis, dan birokrat—dengan pengaruh mereka di dalam pemerintahan—adalah sekutu yang lebih berharga daripada tim sukses yang telah selesai memainkan perannya.
Namun, ini menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendalam: Apakah kesetiaan tidak seharusnya dihargai lebih tinggi daripada sekadar kekuasaan? Plato, dalam Republik, mengajukan gagasan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang memerintah dengan adil, yang menghargai para pembantu setianya sebagai rekan dalam mencapai kebaikan bersama.
Namun dalam kenyataan politik kita, idealisme Plato tampaknya terlalu jauh dari kenyataan.
Para tim sukses yang ditinggalkan mencerminkan realitas yang lebih kelam tentang hubungan manusia dengan kekuasaan. Dalam pemikiran Thomas Hobbes, manusia secara inheren bersifat egois, dan tindakan politik sering kali digerakkan oleh kepentingan diri sendiri.
Politik, dalam pandangan Hobbes, adalah medan perjuangan yang brutal, di mana yang kuat akan terus berkuasa, sementara yang lemah akan tersingkir. Tim sukses, yang selama masa kampanye dianggap sebagai "pahlawan," dalam situasi ini beralih menjadi korban dari hukum besi kekuasaan yang tidak mengenal loyalitas selain kepada kekuasaan itu sendiri.
Namun, filsafat juga mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan terdapat kesempatan untuk refleksi dan perubahan. Kierkegaard, filsuf eksistensialis, berbicara tentang "lompatan iman"—sebuah dorongan untuk melepaskan diri dari kenyataan yang suram dan melompat menuju makna yang lebih tinggi.
Bagi para tim sukses yang merasa ditinggalkan dan dikhianati oleh sistem, mungkin inilah saatnya untuk mengambil lompatan iman itu. Mungkin mereka perlu menyadari bahwa makna hidup mereka tidak dapat ditentukan oleh permainan politik semata, melainkan oleh otonomi dan kehendak bebas mereka sendiri.
Dengan demikian, pertanyaan tentang kesetiaan dalam politik kembali pada intinya: Apakah kita berjuang demi kebaikan bersama, atau sekadar demi ilusi kekuasaan? Bagi mereka yang terlibat dalam Pilkada, terutama para tim sukses yang telah bekerja keras namun tidak mendapatkan imbalan, mungkin inilah saatnya untuk merenungkan kembali motivasi mereka.
Seperti yang dikatakan oleh Albert Camus dalam Mite Sisifus, ada martabat dalam perjuangan, meskipun hasil akhirnya mungkin nihil.
Pada akhirnya, tim sukses yang ditinggalkan setelah Pilkada mungkin merasa tertipu oleh janji-janji kosong. Namun, mereka juga memiliki kesempatan untuk mengambil pelajaran dari pengalaman itu—bahwa kekuasaan sering kali tidak adil, dan kesetiaan tidak selalu dihargai dalam politik yang berorientasi pada hasil.
Seperti Sisifus yang terus mendorong batu ke atas bukit meskipun tahu bahwa batu itu akan kembali jatuh, ada kebebasan dalam memilih untuk terus berjuang, meski hasilnya mungkin tak sesuai harapan.
*) Maulana MPM Djamal Syah, SH, MH adalah Ketua Persatuan Alumni GMNI (PA GMNI) Halmahera Selatan
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected].
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)